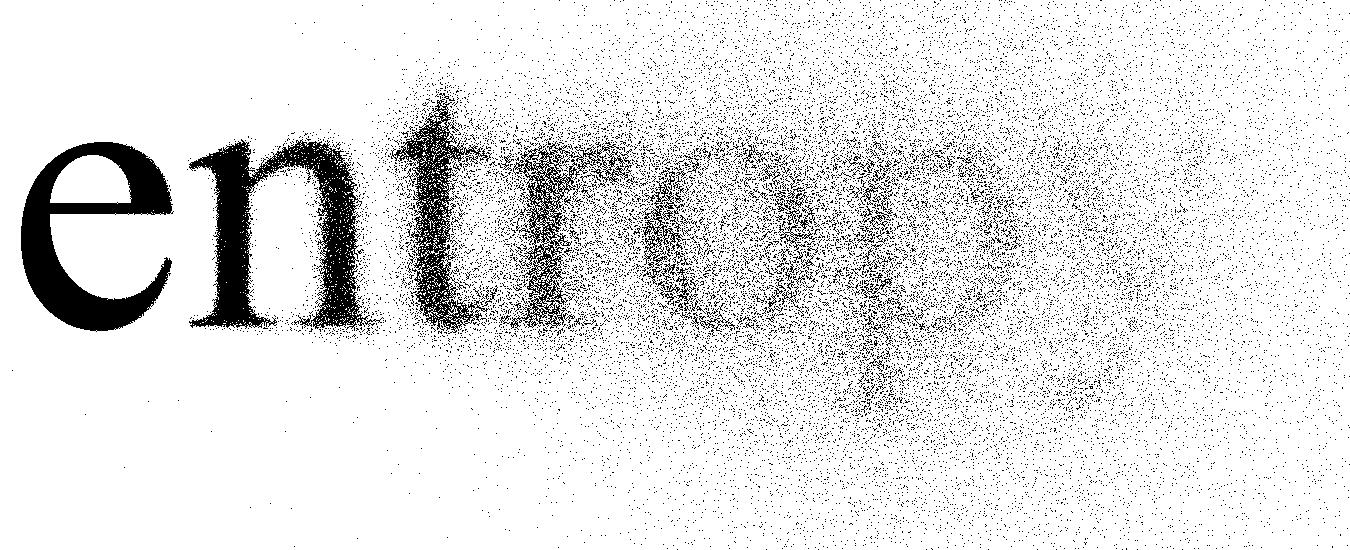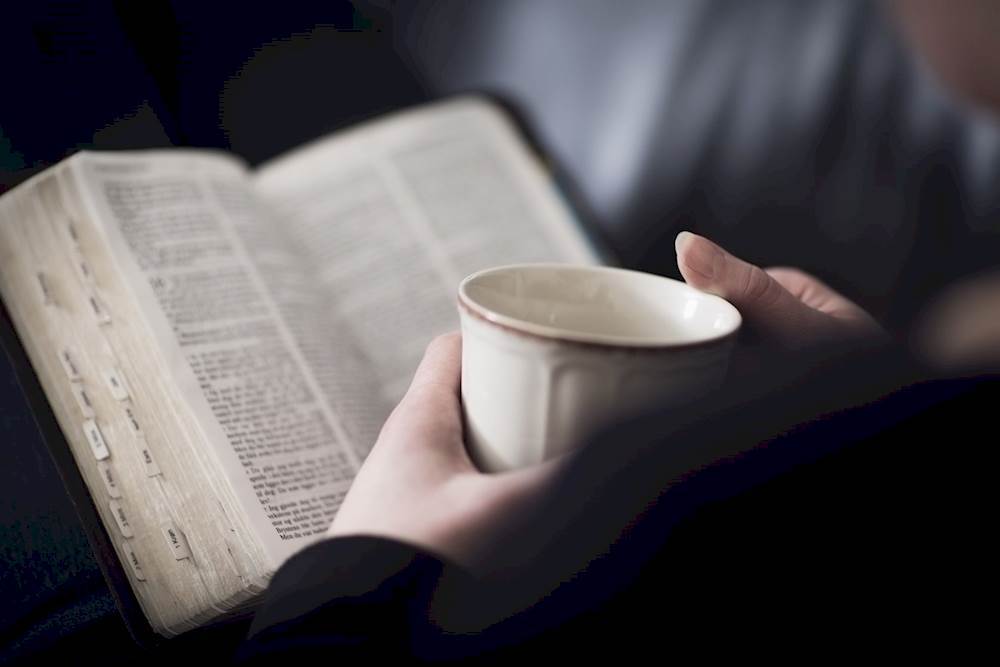--Rin Surtantini
Terusik
oleh diskusi di Whatsapp pribadi dengan salah seorang teman tentang kegiatan
membaca yang hampir setiap saat dilakukan oleh siapapun, membuat saya mengenang
kembali salah satu materi yang saya pelajari di Regional English Language
Center (RELC) di Singapura, sekira lima tahun yang lalu. Saat itu saya
bersyukur, terseleksi sebagai salah satu dari sekian banyak pendaftar untuk mendapatkan
beasiswa mengikuti Professional
Enhancement Program in Pedagogy and Principles of Teaching for Indonesian
Master Trainers of English, karena itu sungguh bermanfaat! Dua bulan tinggal dan belajar dengan
jadwal padat setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 09.00 sampai 16.00 di
negeri singa pada tahun 2015 ini, salah satu materi yang sampai saat ini masih
berkesan adalah yang berkaitan dengan literasi “membaca”.
Ya, setiap
orang yang bersekolah pasti bisa membaca (dalam bahasa yang digunakannya).
Setiap orang mengalami bagaimana ia belajar membaca, mulai dari mengenal huruf,
suku kata dan kata, sampai menjadi frasa atau kelompok kata, kalimat yang utuh,
mengeja, merangkai, dan mengucapkannya dari sebuah teks tulis yang tersedia.
Saya juga ingat, bagaimana dulu keponakan saya yang saya kunjungi di Surabaya,
ketika ia berusia lima tahun, selalu berusaha membaca keras setiap tulisan yang
dilihatnya di pinggir jalan, di baliho, di spanduk, di papan iklan, di
toko-toko, di sepanjang perjalanan kami di atas mobil. Sungguh menarik, dia
secara alami dan spontan mempraktikkan kepandaiannya bahwa dia sudah bisa
membaca.
Peristiwa
yang juga masih saya ingat adalah ketika di Sekolah Dasar berpuluh tahun silam,
ibu dan bapak guru di kelas satu dan dua selalu meminta murid-muridnya secara
bergiliran untuk membaca nyaring (reading
aloud) bahan bacaan yang ada di buku pelajaran Bahasa Indonesia. Nanti,
akan terlihat siapa yang lancar, lantang, intonasinya baik, tidak salah ucap.
Yang masih belum lancar, suaranya pelan, intonasinya kurang baik, ucapannya
masih salah, akan diminta oleh ibu atau bapak guru untuk mengulangi. Begitulah,
pelajaran membaca menjadi salah satu persyaratan di sekolah untuk dapat
memahami pelajaran-pelajaran lainnya.
***
Kembali ke
diskusi saya dengan teman di atas tadi, yang kami perbincangkan adalah: setiap
orang bisa membaca, tetapi apakah setiap orang paham apa yang dibacanya? Diskusi
ini muncul karena dalam sebuah forum komunikasi, sempat terlihat ketidakpahaman
seseorang terhadap apa yang dibacanya, sehingga responnya terhadap topik
pembicaraan menjadi tidak pas, menggok.
Ingatan saya tentang “apa itu membaca” dalam konteks literasi baca tulis tiba-tiba
muncul. Kita banyak membaca apapun, mulai dari yang ringan sampai yang serius,
tetapi mungkin pernah suatu saat kita sendiri mengalami, atau kita menyaksikan
orang lain, bahwa “bisa membaca” belum tentu “paham apa yang dibaca”! Jika memperhatikan
dengan cermat, indikasi ketidakpahaman seseorang akan apa yang dibaca dapat terlihat
pada forum komunikasi yang terjadi, baik komunikasi lisan maupun tulis.
Kita tentu
ingat bahwa beberapa tahun silam, “literasi” sempat menjadi salah satu materi
umum yang wajib diberikan pada diklat-diklat bagi guru, kepala sekolah, dan
pengawas di negeri ini. Di dalam bahan tayang yang wajib disampaikan oleh
widyaiswara pada diklat-diklat ini, terdapat sekian jenis literasi, bukan hanya
literasi baca tulis saja. Sementara itu, yang paling banyak bisa dicontohkan
adalah yang berkaitan dengan literasi baca tulis. Contoh-contoh literasi baca
tulis itu ditampilkan dengan misalnya membuat pojok baca di sekolah yang
didekorasi sedemikian rupa untuk menumbuhkan minat baca, membaca tentang sebuah
topik selama lima belas menit pada pagi hari di dalam kelas, memperbanyak
jumlah buku di perpustakaan sekolah, dan berbagai teori lainnya, ditambah lagi
dengan sekian banyak panduan teknis bagi para guru untuk melaksanakannya di
sekolah, sampai ke lembar evaluasi apakah usaha meningkatkan literasi sudah
dilakukan.
Seiring
dengan perubahan kebijakan dan lain sebagainya, materi literasi dan hal-hal yang
berkaitan dengan itu sudah berlalu dan tidak lagi menjadi “trend” sebagai
materi diklat saat ini. Saya teringat tulisan almarhum Prof. Winarno Surakhmad,
guru besar Universitas Negeri Jakarta dalam buku Pendidikan Nasional: Strategi dan
Tragedi (2009).
Dituliskannya, menerapkan pendidikan tanpa
menghiraukan landasan filosofinya, atau mendalami filosofi pendidikan sebagai
pengetahuan tanpa menghiraukan penerapannya, berarti memilih yang tidak
benar. Menurutnya, secara hakiki, tidak ada aktivitas atau praktik pendidikan
yang dapat berlangsung tanpa dasar filosofi yang sedikitnya terkait dengan
makna kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan; demikian pula sebaliknya, tidak
ada filosofi yang dapat mendalami problematik pendidikan tanpa menjiwai praktik
pendidikan. Filosofi pendidikan yang tidak berkelanjutan ke dalam penerapannya
dalam kehidupan nyata, menjadi mubazir dan tidak layak disebut filosofi
pendidikan.
***
Kegiatan
paling awal yang dilakukan oleh pengajar di RELC Singapura pada materi
“Reading” yang saya alami adalah menumbuhkan kesadaran terhadap apa itu keterampilan
membaca atau reading skills. Dengan
survei yang dilakukannya terhadap peserta program pelatihan ini, sesuatu yang
menggelitik pun muncul: apakah yang dimaksud dengan membaca nyaring (reading aloud) versus membaca untuk
memahami (reading comprehension)? Membaca nyaring sesungguhnya bukan
termasuk keterampilan membaca, melainkan speaking
skills (keterampilan berbicara), karena dalam membaca nyaring, yang ingin
dicapai adalah pengucapan yang benar dan jelas, intonasi yang tepat, kelancaran
dalam mengucapkan, dan nada suara yang sesuai. Inilah yang dilatihkan dan
diajarkan ketika guru-guru meminta muridnya untuk membaca nyaring (reading aloud), jadi tujuannya adalah bukan
untuk memahami apa yang dibaca. Ini
mengingatkan saya ketika mendapat giliran membaca keras ketika di Sekolah Dasar
dahulu.
Pelajaran
membaca yang sesungguhnya adalah reading
comprehension (membaca untuk memahami). Membaca dalam konteks memahami
adalah ketika seseorang melihat teks dan “memberi makna” kepada simbol tertulis
(teks) tersebut. Membaca adalah mengonstruksi makna melalui interaksi dinamis
antara tiga hal, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang sebagai pembaca,
informasi yang diberikan oleh teks, dan konteks yang tersedia. Jadi, untuk
tujuan ini, maka pelajaran “membaca” bukanlah read aloud, tetapi think
aloud.
Kegiatan
berikutnya yang dilakukan oleh pengajar di RELC Singapura pada materi “Reading”
ini adalah melakukan survei terhadap peserta pelatihan, yang antara lain
menanyakan apa yang dilakukan oleh guru dalam pelajaran membaca? Mengajarkan membaca
(teaching reading), ataukah
memberikan tes membaca (testing
reading)? Pertanyaan ini
menggelitik, karena faktanya adalah guru lebih cenderung melakukan “tes membaca”
terhadap murid-muridnya daripada mengajarkan “strategi membaca” untuk
memperoleh makna atau memahami bacaan. Hal ini akan terlihat dari kegiatan
klasik yang dilakukan oleh guru setelah murid-murid membaca, yaitu meminta
mereka untuk menjawab pertanyaan bacaan. Jika murid dapat menjawab pertanyaan sesuai
dengan yang “tersurat” pada bacaan, maka disimpulkan bahwa murid memahami isi
bacaan. Benarkah demikian? Ini sangat berkaitan dengan konstruksi pertanyaan
yang dibuat oleh guru terhadap bacaan yang diberikan kepada murid-murid. Apakah
pertanyaan bacaan itu hanya mengecek “ingatan”, ataukah sampai kepada level
yang lebih tinggi? Setelah tiga tahun kemudian di Indonesia, hal ini saya temukan
mirip pada materi HOTS (higher order
thinking skills) yang menjadi “hot issues” atau materi wajib pada
diklat-diklat guru di negeri ini, bersamaan dengan materi literasi.
Selanjutnya,
pengajar RELC Singapura meminta peserta pelatihan untuk melakukan evaluasi
terhadap bahan-bahan bacaan dalam buku-buku pelajaran Bahasa Inggris yang
diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Indonesia, mulai dari Sekolah Dasar
sampai Sekolah Menengah Atas.
Fokus yang
harus kami lakukan saat itu adalah mengevaluasi konstruksi pertanyaan-pertanyaan
yang ada pada bahan bacaan pada buku-buku pelajaran terbitan Indonesia tersebut.
Evaluasi dilakukan menggunakan taksonomi pada keterampilan membaca. Hasilnya? Sungguh
menggugah. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar pertanyaan yang
diberikan untuk mengecek reading
comprehension (pemahaman terhadap bacaan) setelah murid membaca bahan-bahan
bacaan pada sebagian besar buku penerbit Indonesia, ada pada level literal comprehension, yang jika
disetarakan dengan taksonomi Bloom, ada pada level LOTS (lower order thinking skills), atau C1 (mengingat). Level literal comprehension merupakan salah
satu level rendah yang ada pada taksonomi membaca. Sangat sedikit ditemukan pertanyaan
yang dibuat untuk membuat murid berlatih menganalisis, mengevaluasi,
mengapresiasi, atau melakukan inferensi dan variannya.
Dari fakta
di atas, maka selain “apa yang dibaca” (what
to read), mengajarkan “bagaimana membaca” (how to read) menjadi strategi membaca yang perlu dikuasai dan
diajarkan oleh guru, pendidik, pengajar, sebagai bagian dari penguasaan
literasi baca tulis dalam segala bidang ilmu. Mengajarkan strategi membaca (teaching reading) ini menjadi isu penting dalam pengalaman literasi
baca tulis, bukan sekedar mengetes membaca (testing
reading). Akhirnya, pengecekan terhadap pemahaman membaca (reading comprehension) juga menjadi
bagian penting dalam belajar membaca. Pengecekan ini dilakukan melalui
konstruksi pertanyaan yang tidak hanya melibatkan ingatan murid terhadap yang
tersurat, tetapi juga melibatkan kebiasaan pada level-level berpikir tingkat
tinggi, seperti melakukan inferensi, mengevaluasi, menganalisis, mengapresiasi,
dan berbagai variannya.
***
Bisa
membaca dan paham apa yang dibaca, menjadi dua persoalan penting dalam meningkatkan
“literasi” (baca tulis) sebagai salah satu kecakapan abad 21 dalam pembelajaran.
Dalam konteks yang lebih luas, literasi baca tulis tentu harus terjadi dalam pembelajaran
pada segala bidang ilmu dan pengetahuan, bukan hanya pada pelajaran bahasa. Literasi
baca tulis pun tidak hanya terjadi pada pembelajaran di sekolah, tetapi juga
dalam segala konteks kehidupan, dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi,
dalam bekerja, dengan mengoneksikan landasan filosofis dan praktik. Selamat
berliterasi!
Yogyakarta, 24 Januari 2021.