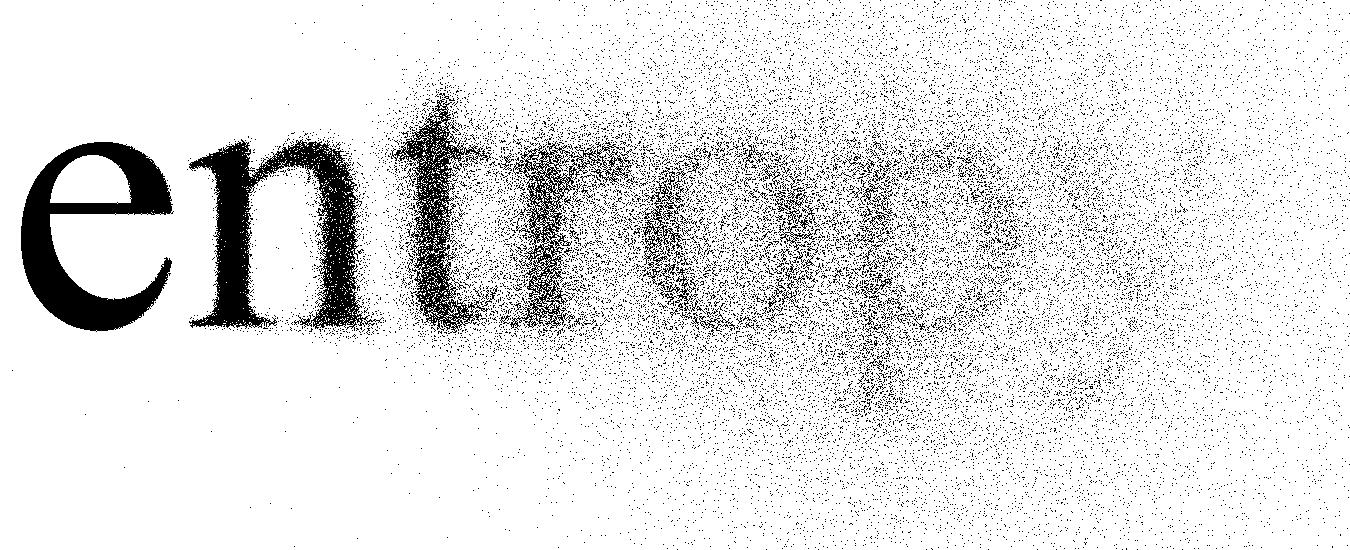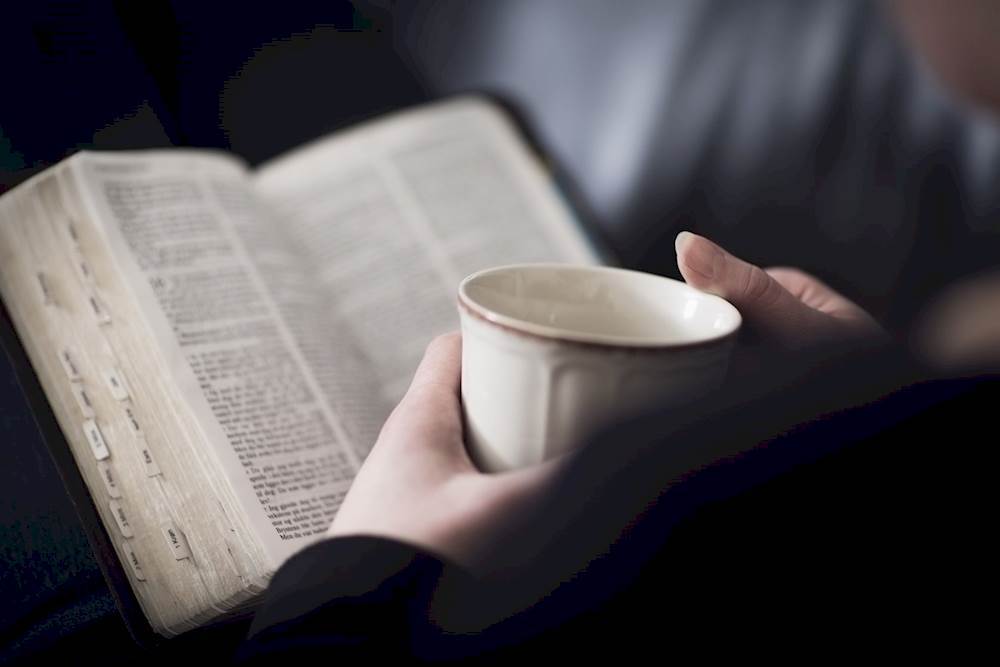---F. Dhanang Guritno
Mengenang 40 hari Mas Kari Hartaya dipanggil Tuhan
Bertahun-tahun bergulat dengan
penyakit diabetes, dua tahun yang lalu terkena serangan stroke, dan akhirnya
perjalanan hidup di dunia ini harus berakhir di ujung tahun 2021.
24 Desember 2021 pagi saat aku bangun tidur kubuka ponsel, betapa terkejutnya aku ketika berbagai grup WhatsApp mengabarkan berita duka meninggalnya saudara, teman, dan sahabat tercinta Mas Kari Hartaya. Sekitar pukul 2.30an dini hari ternyata sebenarnya HPku beberapa kali berdering saat kerabat berusaha menghubungiku untuk mengabarkan berita itu. Namun karena tertidur lelap sedari sekitar pukul 24.00 aku tidak mendengarnya. Setelah bangun barulah aku tersadar bahwa Mas Kari telah dipanggil Tuhan. Antara percaya dan tidak, hari kemarin masih beraktifitas seperti biasa masuk kantor dan sore hingga malam latihan mempersiapkan misa Natal. Memang penyakit diabetes itu sudah disandangnya bertahun-tahun, dan dua tahun yang lalu terserang stroke. Tapi kondisi terakhir itu sepertinya tidak sedang drop.
Saat
itu pikiranku langsung mengingat-ingat hari-hari akhir bersamanya. Sepertinya waktu
itu tidak ada hal yang aneh pada dirinya. Kuingat betul sehari sebelumnya kami
masih makan siang bersama di sebuah warung daerah Gentan Jalan Kaliurang beliau
nampak biasa-biasa saja, hanya saat itu sebenarnya aku agak sedikit heran
dengan tingkahnya. Ketika aku belum selesai minum dia sudah mengajak
cepat-cepat pergi dari situ seperti orang terburu-buru sambil berbicara dalam
bahasa jawa “aku saiki ngapa-ngapa ora
jenak” (Aku sekarang apa-apa selalu tidak betah).
Saya
ingat juga ketika awal Desember ikut kegiatan pemberdayaan SDM BBPPMPV Senbud ke
Bandung, ternyata ada sedikit hal yang aneh darinya. Dengan semangat dia tampak
antusias mengikuti kegiatan itu. Ketika perjalanan pulang rombongan berhenti di
toko oleh-oleh, dengan semangat pula dia memborong oleh-oleh. Aneka makanan
banyak dibelinya. Antri berjubel membeli peuyem dilakukannya. Padahal setahuku
hal-hal sepeti itu dulu tidak begitu suka melakukan. Namun apakah itu suatu
firasat atau bukan hingga saat ini akupun tidak pernah tahu.
Mas Kari dari sudut pandangku…
Terlahir
56 tahun yang lalu, kami mempunyai banyak kesamaan. Kami sama-sama lahir pada
tahun 1965, hanya berbeda bulan. Tinggal
di kota yang sama Bantul. Masih ada hubungan keluarga (ayah beliau adalah kakak
dari ibuku), dalam bahasa Jawa sering disebut nak-sanak, tunggal simbah, atau sepupu. Menurut cerita orang tuaku
dulu, ayahnya memberi nama Kari karena saat itu Presiden Soekarno sedang giat
mencanangkan gerakan hidup “Berdikari” singkatan dari “berdiri di atas kaki
sendiri”.
Dengan
beberapa kesamaan kami tumbuh dari kecil dengan melalui berbagai jalan hidup. Kami
berminat pada hal yang sama, yakni bermain musik. Kebetulan keluarga besar kami
mulai dari simbah, pakde-pakde, om-om sebagaian besar mempunyai hoby bermain musik. Sampai pada akhirnya di
tahun 1983/1984 kami menempuh kuliah pada jurusan yang sama yakni Pendidikan
Seni Musik IKIP Yogyakarta.
Liku-liku
perjalanan menekuni dunia musik banyak kami lalui bersama. Mulai dari bermain
band keluarga, band teman-teman sebaya, keroncong dan musik-musik gereja. Kami
sering berdiskusi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan musik dan kondisi
kehidupan kami yang bukan berasal dari keluarga berada. Berdiskusi bagaimana
kita bisa mencari penghasilan dari bermain musik. Masih kuingat betul kami
selalu membicarakan bagaimana kita berupaya untuk dapat mencari uang dari
bermain musik pada saat kita kuliah dulu.
Penjuangan
mengabdikan diri pada dunia musik
Di
tahun 1984 - 1990an, pada saat kuliah, kami mencari celah-celah pekerjaan free lance dengan menjadi pemain musik
untuk rekaman. Diantaranya kami mencoba bekerja sama dengan TVRI lokal Jogja dan
dengan Komisi Sosial Keuskupan Agung Semarang yang berada di Gereja Katolik Bintaran
waktu itu yang memproduksi lagu-lagu rohani.
Di
TVRI stasiun Yogyakarta kami berjuang merintis menjadi pengisi acara dan
menjadi musisi pengiring penyanyi pada beberapa acara. Yang masih kuingat acara
yang pernah kami iringi antara lain progam hiburan musik: Hiburan Senja,
Visirama, Lagu Pop Daerah dan lain-lain. Sedangkan di KOMSOS kami mengerjakan
iringan musik lagu-lagu rohani yang diproduksi secara komersial dalam bentuk
pita kaset. Kerja keras yang kami lakukan bersama mas Kari pada waktu itu
sedikit membawa hasil. Setidaknya kami tidak terlalu bergantung pada orang tua
untuk sekedar uang jajan dan membeli BBM.
Seiiring
berjalannya waktu sekitar tahun 1989 mas Kari mencoba terobosan baru yakni
bermain live music di café/restaurant dan bar hotel. Suatu hal yang sebenarnya sangat asing bagi kami.
Biasanya kami melakukan rekaman di studio, kali ini mencoba peruntungan untuk
menjadi seorang Entertainer untuk menghibur para pengunjung cafe. Pada saat itu di Jogja memang
sedang marak berbagai café dan restauran serta bar di hotel yang dilengkapi
dengan live music. Berbagai café, restaurant
dan bar di hotel-hotel saat itu seperti wajib memiliki hiburan music secara live. Berbagai tempat itu menyajikan
berbagai format musik yang berbeda-beda. Jika besar seperti hotel-hotel
menampilkan band, namun jika kecil untuk menghemat berbagai hal maka
ditampilkan elekton dengan singer,
atau yang sekarang biasa disebut organ tunggal.
Berawal
dari situlah dia sukses menjalani profesi barunya. Jadwal bermainnya sebagai
pemain keyboard/solo piano maupun
bermain dalam band setiap malam hampir seluruh café, hotel restaurant di
Jogja ini, ada. Sebagai orang yang dekat dengan beliau akhirnya aku pun dengan
segala kekuranganku belajar mengikuti jejaknya. Dan pada tahun-tahun 1990an aku
melakoni hal yang sama. Tentu jika aku tidak dekat secara personal hal itu
tidak akan terjadi. Berbagai motivasi dan dorongan dia lakukan dengan
memberikan materi-materi bermain musik,
repertoar lagu yang belum kukenal, dia dengan sabar mengajariku. Berbagai hal
dilakukan dengan tak jemu-jemunya membujukku terus untuk mau mengikuti
jejaknya. Barangkali tanpa peran serta yang luar biasa darinya aku tak akan
bisa melakukannya.
Mas
Kari adalah seorang Entertainer sejati. Dia telah sukses melakukan pekerjaannya
menghibur orang melalui permainan musiknya. Dia begitu sukses mengiringi orang
menyanyi dari berbagai macam kalangan. Mulai dari orang awam, penyanyi lokal
hingga artis papan atas merasa nyaman ketika menyanyi diiringi permainan musiknya.
Bahkan dia pun menjadi penghibur teman-teman dalam satu panggung ketika ada
yang tidak siap mengiringi suatu lagu. Dengan segenap kemampuannya dia bisa
menggerakkan timnya untuk sukses menjalani pekerjaannya bermain musik. Sungguh Leadership yang luar biasa.
Perjalanan
kami sebagai pemain musik tidak hanya berhenti dari café ke café, bar ke bar,
hotel ke hotel sebagai pemain musik reguler(terjadwal). Kami berjuang juga
sebagai pemain musik by order pada
berbagai event. Artinya kami menjadi pengisi
acara pada event tertentu misalnya Wedding party, gathering perusahaan dan lain-lain.
Ketika
berbagai event di Yogyakarta sekitar
tahun 2000 banyak diisi pertunjukan keyboard
tunggal atau band, saat itu mas Kari mempunyai ide yang cukup brilliant. Dia mengajak aku dan beberapa
teman mencoba terobosan baru yang berbeda yakni format ansambel. Ansambel dan
mini orchestra yang melibatkan juga musisi akademis (bukan otodidak). Mulailah
kami membentuk “Java Ansambel” Format ini berbeda dengan grup lain, yakni
memasukkan unsur orkestra. Ternyata format ini banyak diminati klien untuk
pengisi acaranya seperti pesta pernikahan. Dan hingga saat ini masih eksis, dan
pada hari-hari terkhirnyapun Mas Kari masih sibuk mempersiapkan job wedding yang sedianya dilakukan
tanggal 1 Januari 2022.
Di
luar bermain musik saat mengajar berbagai macam diklat dan bergaul dengan
orang, dia juga sukses menjadi entertainer/penghibur
yang sejati. Hampir semua orang yang mengenal dia secara personal selalu
mengatakan dia adalah orang yang supel, sumeh, dan menghargai orang lain dalam
setiap pembicaraan. Pada berbagai kegiatan pembelajaran mas Kari selalu tampil
mengajar dengan sabar, telaten bukan sekedar memberikan ilmu, namun juga selalu
membuat kelas menjadi hidup dan setiap peserta merasa mendapatkan sesuatu yang
baru dan menghibur. Itulah makanya dalam tulisan ini saya sebut dia adalah entertainer atau penghibur sejati.
Demikian
sekilas perjalanan kebersamaan kami bermusik dengan almarhum Mas Kari. Apapun
yang telah beliau lakukan adalah sesuatu yang terbaik bagi kehidupannya dan
membawa berkah bagi orang lain. Hingga saat ini saya mempunyai kesimpulan dia
adalah orang yang konsisten pada pengabdian hidup yang telah dipilihnya yakni
musik. Tanpa peran serta beliau, mungkin saya tidak akan bergulat juga dalam
bidang musik ini. Dialah saudara, teman, sahabat dan guru terbaikku. Dia sangat
berjasa bagi perjalanan panjang hidup dan kehidupanku.
“Selamat jalan Mas
Kari, berbahagaialah dan bermusiklah dengan para kudus di Surga…..Amin”.