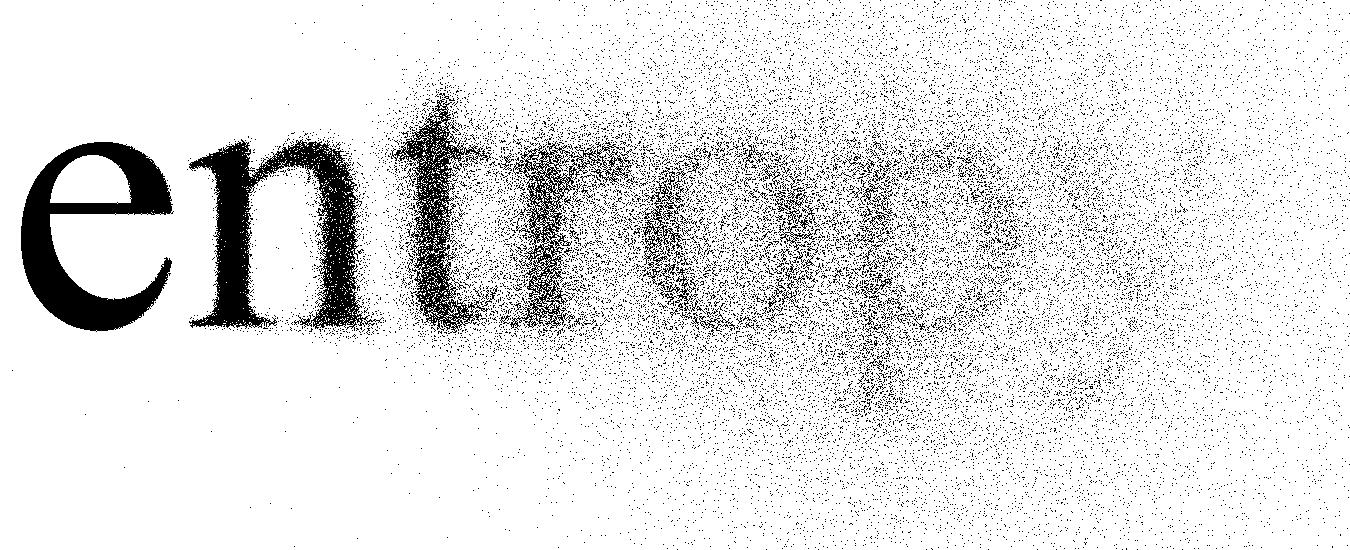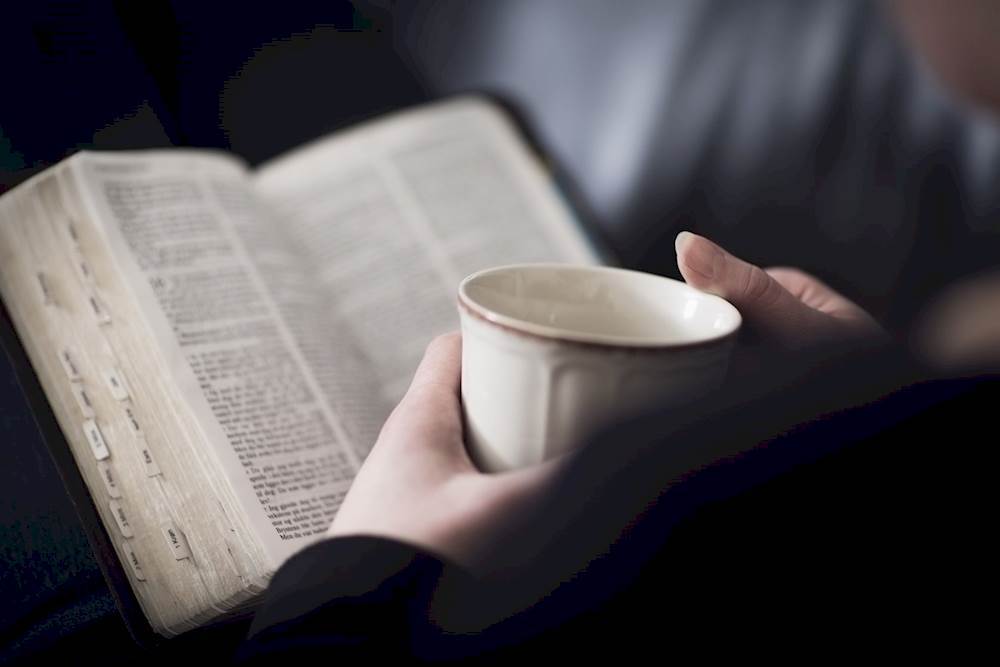--Rin Surtantini
Sebuah kesadaran
Mengikuti sebuah
ToT mengenai isu profil pendidikan selama tiga hari baru-baru ini, membuat saya
sedikit terpancing untuk “berpikir”. Sudah sering saya dengan kesadaran penuh
tidak tertarik atau meminta ijin mundur dari kegiatan-kegiatan yang secara
keyakinan atau prinsip bagi saya adalah kegiatan yang akan membuat saya
tertekan, gelisah, merasa menjadi sangat bodoh, menjadi tidak logis, tidak
punya dasar atau pegangan, bingung, kuatir, tidak mampu, malu, dan jenis-jenis
perasaan negatif lain yang tidak produktif semacam ini. Dengan memutuskan tidak
terlibat dalam kegiatan-kegiatan semacam itu, saya justru sering merasakan bahwa
perasaan negatif tidak menyerang hati kecil saya, dan saya jadi bisa fokus
kepada hal-hal yang menggembirakan diri karena itu berdampak baik bagi mereka yang
membutuhkan.
***
Memahami apa itu data vs. fakta
Rasa
ketidakpahaman saya itu memicu saya untuk “berpikir”. Mungkin ini baik bagi
saya untuk memahamkan diri sendiri mengenai apapun hal yang dikatakan berbasis
data. Kata berbasis “data” itu sendiri justru mengingatkan saya mengenai
pemahaman saya tentang apa itu “data” ketika saya sekolah dulu. Data ada yang
berjenis kualitatif, ada yang berjenis kuantitatif. Itulah sebabnya ada
penelitian kualitatif, dan ada penelitian kuantitatif, sehingga metode atau
cara pengumpulan datanya akan berbeda. Demikian pula analisis data dari kedua
jenis data ini juga berbeda, sebelum akhirnya dimunculkan kesimpulan dari kedua
penelitian tersebut.
Kita sering sulit untuk dapat membedakan antara apa itu “data” dengan apa itu fakta”. Fakta adalah pernyataan tentang sebuah realita, atau tentang sebuah kenyataan. Orang yang menceriterakan suatu kejadian adalah orang yang sedang mengemukakan fakta-fakta, yaitu pernyataan-pernyataan dari dirinya tentang suatu kenyataan atau realita. Misalkan, ada sebuah institusi meraih sertifikat wilayah bebas korupsi, itu adalah sebuah kenyataan. Prestasi ini kemudian dibicarakan oleh banyak orang. Coba perhatikan: pernyataan tentang kenyataan yang sama ini, yaitu peraihan sertifikat wilayah bebas korupsi, dikemukakan atau dihasilkan oleh setiap orang lewat sudut pandangnya masing-masing. Kenyataannya sama, tetapi komentar, pernyataan, ulasan, atau berita yang dihasilkan mengenai fakta yang sama ini sifatnya “subyektif“, karena sebuah kenyataan atau realita yang sama dapat saja dikemukakan dengan cara-cara yang berbeda. Dalam konteks ini, wacana yang dihasilkan oleh setiap orang yang memberitakan peraihan sertifikat wilayah bebas korupsi ini tidak akan pernah bisa persis sama. A mengemukakan begitu, B menyatakan begini, dan C mengemukakan begitu dan begini.
Di sisi lain, benarkah “fakta” itu hanya bersifat subyektif? Tentu tidak. Fakta juga dapat disebut “obyektif” ketika pernyataan tentang fakta ini didasarkan pada kenyataan atau realita tertentu. Jika ada pernyataan yang tidak didasarkan pada suatu realita atau kenyataan, maka pernyataan tersebut lemah dan tidak dapat dikatakan sebagai fakta. Pernyataan lemah dan bukan fakta semacam inilah yang kita sebut sebagai sebuah kebohongan, karangan, isapan jempol, hasil imajinasi, khayalan, atau dapat juga sebuah fitnah. Semua pernyataan manusia, baik itu verbal yang bersifat lisan maupun tulis, merupakan tindak tutur. Tindak tutur adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam berkomunikasi menggunakan bahasa verbal. Tindak tutur ini terdiri dari tiga aspek, yaitu perangkat kebahasaan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu, tindakan atau makna yang terdapat di balik perangkat kebahasaan tersebut, dan hasil atau efek dari pernyataan tersebut. Menarik untuk diselidiki ketika seseorang bertindak tutur. Akan diketahui bagaimana ia menyatakan suatu isu secara verbal, apa makna di balik pernyataan tersebut, dan apa efek, hasil, atau pengaruh dari pernyataannya tersebut. Namun, tulisan saya ini tidak akan membahas hal ini.
Kembali ke “data” dan “fakta”. “Fakta” dari uraian di atas dapat dikatakan bersifat subyektif dan sekaligus juga obyektif. Sehubungan dengan ini, pertanyaannya adalah, apakah “fakta” itu adalah “data”? Fakta dapat menjadi data, akan tetapi ingat bahwa “tidak semua fakta dapat menjadi data”. Mengapa? Karena data adalah fakta-fakta yang relevan, yang secara logis berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan untuk dijawab. Jadi data harus merupakan fakta-fakta yang telah dipilih atau diseleksi berdasarkan azas relevansi terhadap persoalan atau masalah yang ingin dijawab atau ditemukan solusinya.
***
Maka, ketika minggu
lalu saya mengikuti ToT penjaminan mutu melalui perencanaan berbasis data, yang
berkaitan dengan rapor sekolah dan profil pendidikan, saya merasa bahwa sebagai
peserta ToT, saya tidak dapat menjelaskan esensi dari apa yang dimaksud dengan
“berbasis data”. Apa yang dimaksud dengan “data” dalam hal ini? Data yang
bagaimanakah yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data (yang tentunya ada)?
Bagaimanakah bentuk instrumennya sehingga kita tahu komponen atau aspek-aspek
apa sajakah yang dipakai sebagai alat ukur dalam pemetaan mutu sekolah? Jika
dikatakan bahwa data diperoleh dari sekian sumber data yang sangat luas,
bagaimanakah pengelolaan data ini pada saat analisisnya, sehingga satuan
pendidikan harus menerima saja hasilnya berupa rapor satuan pendidikan?
Dikatakan, bahwa rapor sekolah dan profil pendidikan tersebut valid digunakan sebagai bahan untuk perencanaan karena telah melalui proses simulasi, uji coba, disusun oleh berbagai pakar pendidikan, dan dihasilkan dari pelaksanaan Asesmen Nasional yang sangat masif dan melibatkan seluruh elemen pendidikan yang ada, seperti sekian ratus ribu sekolah, sekian juta guru, dan sekian juta siswa. Asesmen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi tersebut menggunakan instrumen AKM (asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar).
Sekolah, dalam hal ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menerima “data-data” pada rapor sekolahnya, dan tak punya ruang untuk menyanggah, apapun itu, meskipun ingin sekali menyanggah. Di sini saya berpikir, jangan-jangan ketika sekolah sebetulnya menolak “data-data” yang ditampilkan pada rapor sekolahnya, inilah makna dari bedanya “data” dengan “fakta” yang saya tulis di atas. Misalkan, faktanya benar, bahwa guru menjawab “tidak terlibat” ketika ada indikator pada instrumen yang menanyakan apakah ia terlibat dalam kegiatan tertentu, maka itu akan berpengaruh terhadap nilai pada item tersebut. Sementara, fakta lain yang terjadi di sekolah tersebut adalah bahwa sesungguhnya banyak guru yang terlibat pada kegiatan yang ditanyakan di instrumen, tetapi guru-guru tersebut kebetulan tidak mengisi instrumen. Dan sekian contoh lain mengenai makna “data” dan “fakta” ini, yang secara tidak langsung diungkapkan oleh penerima rapor sekolah tersebut.
Dari sisi peserta ToT seperti saya, yah… kita sebagai peserta ToT pun hanya menelaah rapor sekolah yang “given” tersebut. Peserta ToT ini (katanya) nanti diproyeksikan akan membantu dan mendampingi sekolah dalam merencanakan perbaikan mutu sekolah berdasarkan data rapor sekolah tersebut. Selanjutnya, pendamping membantu sekolah mengidentifikasi akar masalah, memberikan alternatif solusi, memilih alternatif solusi, dan menyusun perencanaan kegiatan peningkatan mutu sekolah. Sementara berdasarkan simulasi yang dilakukan pada ToT untuk kegiatan pendampingan ini, saya (pribadi) merasa sangat sulit dalam membaca “data-data” pada rapor sekolah… dan saya juga menemukan bahwa data tertentu pada rapor tersebut tidak sinkron dengan data lainnya yang berkaitan.
Oh, my God. Apa yang terjadi sesungguhnya pada perencanaan berbasis data ini? Saya berusaha memahamkan diri, bersama beberapa teman sesama peserta. Untuk tidak menyalahkan siapa-siapa, saya hanya dapat mengatakan pada diri saya sendiri, bahwa saya sadar saya telah melakukan kesalahan, yaitu tidak fokus mengikuti ToT karena saya “menyambi” dengan pekerjaan online, yaitu menilai essay yang menuntut saya untuk berkonsentrasi penuh. Akibatnya, saya menjadi tidak paham sama sekali esensi dari ToT ini, karena saya telah mendua dan bercabang!
Yogyakarta, 3
April 2022.
(Renungan
personal pada awal Ramadhan)